Saya bersama 9 peserta Media Field Trip di event Explore Destinasi Pulo Aceh diangkut dengan KM Aroeh Bintang dari Dermaga Lamteng, Pulo Nasi. Kapal motor ini biasanya dipakai untuk transportasi masyarakat Pulo Nasi ke Banda Aceh, tapi hari ini akan menjadi kendaraan utama untuk memuluskan kegiatan yang langka bagi penduduk kepulauan terbarat tersebut.
Kapal melaju ke balik pulau untuk mencapai pulau satu lagi yang lebih besar: Pulo Breueh. Saya dapat menatap Sabang di timur saat kapal hendak memasuki mulut Teluk Lampuyang di barat, usai menempuh 20 menit pelayaran di lautan tenang.

Permukaan air hijau berkilau oleh lekuk-lekuk bening, menjadi cermin bagi saya ketika lihat ke bawah dari dek kapal, hingga ditambatkan di dermaga kayu. Kami kumpul di depan kedai tak jauh dari dermaga.
Sejenak kemudian Don Paloh muncul. Kami berkenalan sembari menunggu semua driver lain tiba. Ia bilang, semua pemandu sudah dikabarkan sebelumnya untuk stand by jam 8 pagi di depan kedai kopi Dermaga Lampuyang.
Eksplorasi potensi wisata Pulo Breueh pun dimulai tepat jam 9 meskipun seorang sopir belum muncul. Saya menjadi penumpang kedua pada salah satu sepeda motor, hingga diturunkan di depan sebuah kedai kelontong.
Ada seorang pria baru siap isi bensin untuk sepeda motor bebek. Supra Fit keluaran 2006 dengan body tak lengkap. Mungkin yang terjelek di antara yang lain. Dan mungkin sopir berusia tertua di antara yang lain juga.
Namun itu akan jadi pengalaman berbeda bagi saya, dibanding kawan-kawan media yang lain—termasuk Yudi Randa, blogger Aceh lainnya yang juga mendapat undangan di event ini.
Langsung saja saya dekatinya dan perkenalkan diri. Namanya Fauziyun, berkulit cokelat. Ia mengenakan kemeja hitam dan celana training (seragam olahraga): setelan yang sederhana.
Tanpa basa-basi, saya dipersilakan duduk di belakangnya. Joknya masih empuk. Kami langsung berangkat. Saya berharap dia berikan banyak informasi dalam perjalanan kami mencapai Meulingge, desa terluar di Pulo Breueh yang sudah terkenal dengan iconic tourism site, Mercusuar William’s Torrent.
Ditugaskan sebagai pemandu wisata, akan menjadi pengalaman baru bagi duda dua putri ini yang selama ini hanya bekerja serabutan. Saya penasaran bagaimana ceritanya dia bisa menjadi tour guide hari ini.

Kamis malam lalu, beberapa pria Desa Lampuyang tengah melepas penat di warung kopi—satu-satunya pusat keramaian di desa yang terletak di pulau paling barat Indonesia, Pulo Breueh—lebih barat dari Sabang. Fauziyun salah satu di antara mereka.
“Kata Don Paloh, desa kami akan kedatangan tamu dari NGO hari Sabtu. Jadi butuh sepuluh orang beserta sepeda motor untuk menjadi pemandu tamu itu. Apakah Bang Fauzi bersedia, tanya teman Si Don.”
Fauziyun bercerita sambil mengemudi hati-hati di atas jalan desa yang bebatuan.
“Boleh, jawab saya. Apalagi bawa tamu NGO dibilangnya. He-he.”
Saya ikut tertawa kecil. Kepadanya saya jelaskan bahwa kami bukan orang NGO (Non-Govermental Organization) atau sering disebut LSM di Indonesia.
Kami bukanlah pemain Let’s Get Rich NGO yang datang untuk bangun daerah terpencil tanpa menyesuaikan konsep proyeknya dengan kebutuhan masyarakat setempat.
***
Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, bersama Kota Sabang, resmi masuk dalam wilayah Kawasan Sabang semenjak tahun 2000. Pulo Weh, Pulo Klah, Pulo Rubiah, Pulo Seulako, Pulo Rondo, Pulo Breueh, Pulo Nasi, dan Pulo Teunom, ditargetkan menjadi daerah mata pencaharian masyarakat. Kawasan ini berbatasan dengan Teluk Benggala di utara, Samudera Hindia mengapit dari barat dan selatan, serta Selat Melaka dari timur. Cukup potensial untuk dikembangkan menjadi Pelabuhan Bebas.

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) bertugas melaksanakan pengembangan Kawasan Sabang. Membangun infrastruktur dan mempromosikan ragam potensi kawasan. Itu pula salah satu tujuan digelarnya Explore Destinasi Pulo Aceh pada 14 November 2015. Dihadirkan media nasional, lokal, dan juga travel blogger Aceh, untuk mengubek-ubek kecantikan pulau yang masih terpendam.
“Explore itu Pak, memperkenalkan sisi menarik tentang tempat dan masyarakat di Pulo Aceh ke orang banyak. Nanti kami akan menuliskannya di koran, menayangkannya di tivi, dan sebagainya. Dengan tujuan setelah acara ini akan ada lebih banyak tamu yang datang ke Pulo Aceh, lebih banyak dari hari ini.”
Fauziyun mengiyakan sambil terus mengendarai di jalan lorong Desa Paloh. Tiba-tiba, motornya tersendat-sendat. Dan mati. What’s wrong?
Saya kira habis minyak, padahal dia baru saja isi bensin sebelum tur.
“Ini businya harus diganti,” jelasnya.
Duh, Pak! Sudah tahu ada tamu kenapa tidak disiapkan motornya lebih dahulu?
Saya sempat kesal, tapi tak ingin saya tunjukkan ekspresi ini kepadanya. Cuma di hati aja. Untungnya dia sudah siaga, busi baru segera dikeluarkannya dari bawah jok. Pasti ada hikmahnya. #positive thinking klasik.
Sementara dia memperbaiki motor, saya berlari kecil ke belakang, melihat aktivitas petani di tepi laut. Inilah pemandangan yang unik di Pulo Breueh. Di beberapa titik, ada lahan persawahan ditumbuhi padi, yang bersisian dengan lautan.

Pria dan wanita bertudung membungkuk. Menanam tunas padi. Aktivitas ini mengingatkan saya pada anekdot tentang perbedaan Pulo Nasi dan Pulo Breueh.
Kata “breueh” bermakna beras dalam Bahasa Indonesia, sementara nasi berarti “bu” dalam Bahasa Aceh. Kamu tahu kan duluan ada beras baru bisa ditanak menjadi nasi. #Dan bikin nasi dulu baru bisa dibuat bubur.
Dulunya Pulo Aceh ini dihuni oleh para pendatang dari daratan Aceh, sebelum seramai hari ini—ya setidaknya sekarang sudah ada 5 desa di Pulo Nasi dan 12 desa di Pulo Breueh.
“Orang yang datang ke Pulo Nasi hanya membawa nasi dan tidak berusaha mencari lebih. Sedangkan orang yang merantau ke Pulo Breueh tidak memadai dirinya dengan nasi yang dibawa, tapi berusaha untuk menghasilkan beras.”
Jelas di depan mata saya, segelintir masyarakat Pulo Breueh tengah berusaha menanam bakal beras: padi. Di Pulo Nasi, yang cenderung lebih dekat dengan Banda Aceh dan luas wilayah yang kecil, hanya saya temukan lahan padi di Alue Riyeueng ketika saya keliling Pulo Nasi pada Januari 2015.
Sebaiknya dibaca: Pantai Nipah Pulo Nasi, Mandinya itu di sini
Saya tidak membenarkan anekdot itu. Tapi ketika lima menit kemudian mesin motor Fauziyun kembali meronta-ronta, saya dapati beberapa persawahan di desa-desa selanjutnya, seperti Desa Blang Situngkoh dan Ulee Paya.
Debu membedaki wajah saya—yang tak pernah pakai bedak ini, preeet :D—oleh bekas laju truk pengangkut bongkahan batu gunung dan material pembangunan proyek. Salah satunya ialah Pelabuhan Ikan bertaraf internasional yang tampak jelas dari jalan desa.
Jalanan mulai mulus ketika memasuki Desa Gugop. Pun keindahan tersembunyi mulai terlihat dari jalan menanjak antara desa ini dengan Desa Rinon. Teluk yang luas menciptakan pantai yang melengkung. Berpasir putih. Dengan gradasi laut biru dan toska memanjakan mata dari jauh. Pantai Balue dan Pantai Deumit.

“Masyarakat jarang mandi di Pantai Balue. Tapi bule yang datang sesekali ke Pulo Aceh sering mandi di sana,” sebut pria berusia 48 tahun ini.
Beragam pepohonan di sekeliling jalan bagai rambut keriting lebat yang dicat hijau. Aroma hutan tropis cukup menawarkan polusi yang dilepaskan 10 sepeda motor.
Hanya beberapa menit berkendara naik-turun lereng bukit melewati Pantai Balue, kami kembali disambut panorama pantai yang serupa dari ketinggian jalan. Pantai Dedemit Deumit. Pantai dengan nama yang sama juga ada di Pulo Nasi.
“Deumit itu kami artikan sebagai tempat yang sepi dari kunjungan orang. Di pantai itu hanya didatangi penyu yang bertelur pada musim tertentu. Warga Rinon biasanya menunggu momen itu,” jelas Fauziyun, dalam Bahasa Aceh khas Aceh Besar yang sulit dituliskan ejaannya.
Sebaiknya dibaca: Pantai Deumit Berlumur Sunrise
Satu sisi, sebuah keberuntungan jika sempat ke Pulo Breueh pada musim penyu bertelur. Kamu akan menikmati lezatnya kandungan telur penyu. Tapi di sisi lain, ini menjadi topik berat bagi kalangan aktivis lingkungan. Harus ada solusi agar penyu terus bertelur dan masyarakat tidak mengkonsumsi semua telur itu.
Rinon ialah nama desa selanjutnya sebelum kami mencapai desa terbarat, Meulingge. Konon nama “Rinon” berasal dari lafal “RI Nol”, karena desa ini dianggap tapal batas RI di posisi paling ujung barat.
“Entah karena kebijakan politik atau hal lain, situs KM 0 dibuat di Sabang,” kata panitia Explore Destinasi Pulo Aceh semalam.
Kami melihat “KM 0” di persimpangan jalan menuju Meulingge. Ini mungkin sekali menunjukkan bahwa titik nol di ujung barat Indonesia sesungguhnya ialah Pulo Breueh, bukan Sabang. Secara geografis memang, pulau ini berada di paling barat.

Desa Meulingge lantas kami masuki. Jalan desa beraspal yang mulus menjadi jelek oleh tumpukan kotoran lembu di sekujur badan jalan. Ranjau darat!
Sayangnya, tak ada lagi aktivitas belajar-mengajar di SD Meulingge saat kami tiba siang Sabtu itu. Di depan sekolah, jalanan gunung menanjak, menanti. Itulah jalur untuk mencapai Mercusuar William’s Torrent.
***
Sejauh titik ini, berdasarkan amatan dan beberapa penilaian orang yang sudah ke Pulo Breueh, saya melihat Pulo Breueh menyimpan potensi besar pada wisata lingkungan. Pulo Breueh tak butuh dihias sedemikian rupa layaknya Destinasi Wisata Sabang. Tetapi cukup dengan mengangkat sisi local wisdom (kearifan lokal)-nya, serta mengedukasikan kesadaran wisata kepada masyarakat.
Ketertinggalan atau “Pulo Breueh apa adanya” dalam bahasa lembut adalah kearifan lokal yang akan diminati wisatawan. Tak perlu repot-repot mencari investor untuk bangun cottage, homestay, hotel, apalagi resort.
Rumah-rumah warga adalah akomodasi bagi wisatawan itu sendiri. Kita boleh berkaca pada peraturan masyarakat Baduy Dalam di Banten yang misalnya melarang turis memotret kegiatan mereka. Kita patut melupakan kebebasan di Sabang atau pun Lombok yang dibobol budaya asing. Pihak terkait butuh memoderasi setiap pelaku usaha maupun wisatawan yang datang.
Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Pulo Breueh seperti: harus berdiri di ujung Dermaga Lampuyang dan wajib kelihatan Pulau Weh untuk mendapatkan sinyal telepon seluler; turis tidak boleh bawa sepeda motor dan makanan dari luar ke Pulo Breueh tetapi menggunakan jasa lokal; dan menyaksikan penampilan Rapai Daboh dari masyarakat Meulingge, adalah pengalaman-pengalaman yang patut dijual ke turis domestik maupun mancanegara. Sosialisasi sadar wisata semacam itu pun perlu dilakukan oleh pelaku wisata kepada masyarakat sebelum semua paket-paket itu dijalankan.
Jujur, peluang itu sangat terbuka lebar!
[Bersambung]
Writer: Makmur Dimila
Berjalanlah… dan ceritakan pengalamanmu 🙂








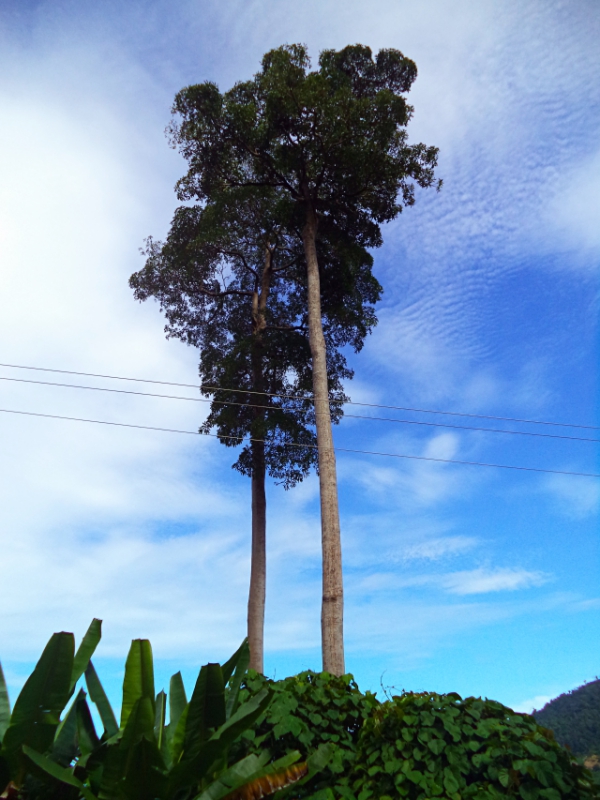
jadi kapan kita ke sini lagi?
Akhir tahun yuk… 😀